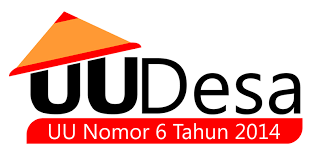Rabu, 18 Desember 2013, hari masih pagi—jam menunjukkan sekitar pukul 09.00 WIB ketika gedung DPR RI di kawasan Senayan Jakarta sudah mulai ramai didatangai “tamu” tak diundang.
Sebagian mengikat kepala, sebagian lain begitu tiba langsung membentangkan spanduk. Ya, mereka para perangkat desa, datang dalam jumlah ribuan orang.
Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air. Datang ke gedung DPR hendak mengawal proses pengesahan RUU Desa, yang hari itu jadwalnya akan disahkan dalam sidang paripurna. Mereka sudah lelah, tujuh tahun berjuang, tujuh kali pengesahan ditunda. Kali ini mereka tak ingin tertunda lagi.
Dan ketika pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu, mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang, suara sorak soraipun terdengar dari kursi balkon, tempat mereka mengikuti jalannya sidang. Beberapa dari mereka saling berpelukan, bahkan ada yang matanya berkaca-kaca. Maklum, UU Desa ini begitu berarti bagi mereka. Sebagai perangkat pemerintah di lapis paling bawah namun selama ini kurang diperhatikan kesejahteraannya, pengesahan UU ini memberi angin segar.
Pasal 72 UU Desa mungkin menjadi primadona buat para Kades ini. Di pasal itulah ditegaskan bahwa negara—melalui APBN akan mengalirkan dana ke desa. Jumlahnya, minimal 10% dari dana transfer daerah dalam APBN setiap tahunnya. Dengan asumsi dana transfer daerah pada APBN 2014 senilai Rp592 triliun dan saat ini terdapat 72.944 desa, maka rata-rata setiap desa akan menerima lebih dari Rp800 juta/tahun.
Meski besaran tiap desa tidak dibuat sama—memperhitungkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luasan wilayah dan kesulitan geografis, namun perbedaannya tetaplah tidak terlalu banyak dari angka itu. Artinya, setiap tahun setiap desa akan menerima aliran dana ratusan juta. wow
Banyak yang bersyukur, menyambut dengan perasaan lega pengesahan UU Desa ini, tapi tak sedikit yang prihatin. Alasannya, dengan kualitas SDM perangkat desa yang rata-rata masih sangat rendah—apalagi soal managemen, akuntabilitas dan transparansi keuangan, bukan tidak mungkin fasilitas uang jumbo dari pemerintah pusat ini justru menjadi jebakan menuju penjara, karena ketidakmampuan para kades menghadapi audit BPK.
Dalam pertanggungjawaban keuangan desa kita merujuk UU No.17/2013 tentang Keuangan Negara, UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No.15/2006 tentang Badan Pemeriksa Kuangan (BPK).
Berdasarkan tiga UU di atas, seperti halnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah), jika kepala desa mengajukan anggaran desa dan disetujui, maka penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam audit yang dilakukan BPK. Fakta selama ini para Kepala Desa yang mendapatkan bantuan program dari APBN tidak pernah diaudit BPK karena mereka tidak menggunakan dana secara langsung dari APBN tapi dalam bentuk program yang sudah jadi.
Karena itu—tanpa bermaksud memberi peluang ikut campurtangan, menurut penulis, pemerintah daerah harus terlibat membimbing, untuk mengatur berapa persen maksimal dari anggaran desa yang boleh untuk belanja aparatur desa, berapa persen minimal harus digunakan untuk peningkatan pelayanan publik, dan berapa persen minimal untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
Akan lebih baik lagi kalau selang waktu satu tahun—sambil menunggu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan, pemerintah daerah mulai melakukan pelatihan managemen keuangan bagi para perangkat desa ini, sehingga saat uangnya turun, mereka sudah tahu cara membuat perencanaan, pengelolaan, pengawasan sampai target yang ingin dicapai dari penggunaan uang itu.
Penulis Firdaus Masrun
Baca juga Opini lain:
KTP Elektronik
Kebiri, Tepatkah ?
Testimoni Freddy
Awas Narkoba
Menteri Arcandra, Kegaduhan Baru
Warung Elektronik
Calon Tunggal
Maaf
Puasa, Bersihkan Hati
Pilkada Serentak
Zigzag
Hak Memilih
UU Desa
DOB, Buah Simalakama